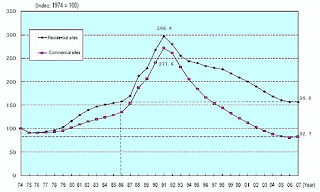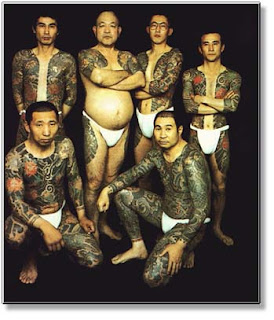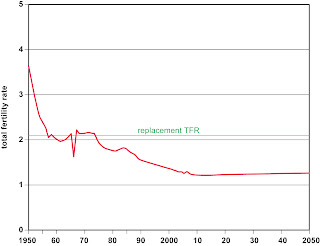Beberapa hari ini, media massa di Jepang memuat berita tentang Naoko Yamazaki. Ia adalah astronot perempuan Jepang yang mampu membetot perhatian publik. Kesuksesannya adalah sebuah fenomena, karena Yamazaki adalah juga seorang ibu rumah tangga. Dalam kultur masyarakat Jepang, tak banyak ibu rumah tangga yang bisa meraih sukses seperti dirinya. Meski Jepang adalah negara modern, pandangan terhadap kaum perempuan masih tradisional. Nilai yang masih dipegang adalah bahwa kaum perempuan itu “konco wingking”(teman di belakang) yang tugas utamanya mengurus rumah dan anak. Oleh karena itu, fokus pemberitaan tentang Yamazaki bukan tentang perannya di ruang angkasa, namun lebih pada perannya dalam kehidupan keluarga.
Beberapa hari ini, media massa di Jepang memuat berita tentang Naoko Yamazaki. Ia adalah astronot perempuan Jepang yang mampu membetot perhatian publik. Kesuksesannya adalah sebuah fenomena, karena Yamazaki adalah juga seorang ibu rumah tangga. Dalam kultur masyarakat Jepang, tak banyak ibu rumah tangga yang bisa meraih sukses seperti dirinya. Meski Jepang adalah negara modern, pandangan terhadap kaum perempuan masih tradisional. Nilai yang masih dipegang adalah bahwa kaum perempuan itu “konco wingking”(teman di belakang) yang tugas utamanya mengurus rumah dan anak. Oleh karena itu, fokus pemberitaan tentang Yamazaki bukan tentang perannya di ruang angkasa, namun lebih pada perannya dalam kehidupan keluarga.Yamazaki, wanita berusia 39 tahun, yang kini bertugas sebagai insinyur stasiun ruang angkasa, harus meninggalkan putrinya yang baru berusia 7 tahun, bernama Yuki, dan suaminya, Taichi, yang secara sukarela meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus anak dan rumah. Taichi meninggalkan pekerjaannya sebagai insinyur perancang software untuk secara “full time” mengurus rumah dan mendukung karir istrinya. Keduanya telah menikah selama 11 tahun, tepat sesaat setelah Yamazaki terpilih dalam program astronot Jepang.
Televisi di Jepang berulangkali menayangkan Taichi, sang suami, sedang mencuci beras untuk makan malam dan mencuci pakaian, sebuah tugas yang sangat aneh untuk pria di Jepang. Media massa kemudian menjuluki Yamazaki sebagai “Mom Astronaut”, julukan yang tidak membuatnya senang, karena kurangnya apresiasi media pada sang suami. Dalam sebuah wawancara, Yamazaki mengatakan bahwa selama 11 tahun ini, ia tak mungkin mencapai karir yang sukses tanpa dukungan suami. Ia menempatkan suaminya tetap sebagai kepala keluarga yang sangat ia hormati. Meski dalam praktiknya, ia mengakui tak mudah.
 Kisah Yamazaki ini membangkitkan kesadaran tentang semakin meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kaum perempuan, pada ujungnya, memiliki kesetaraan derajat dengan kaum pria. Kalau melihat pada kehidupan ekonomi, kaum perempuan di Jepang memang bukan kaum yang terpinggirkan. Hak sosial, politik, maupun kesehatan (biasanya dilihat dari angka kematian ibu yang melahirkan), semuanya sama, bahkan lebih baik dari kaum pria. Namun dalam peranan mereka di pekerjaan dan perusahaan, nilai-nilai tradisional kerap masih dipegang oleh banyak keluarga.
Kisah Yamazaki ini membangkitkan kesadaran tentang semakin meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kaum perempuan, pada ujungnya, memiliki kesetaraan derajat dengan kaum pria. Kalau melihat pada kehidupan ekonomi, kaum perempuan di Jepang memang bukan kaum yang terpinggirkan. Hak sosial, politik, maupun kesehatan (biasanya dilihat dari angka kematian ibu yang melahirkan), semuanya sama, bahkan lebih baik dari kaum pria. Namun dalam peranan mereka di pekerjaan dan perusahaan, nilai-nilai tradisional kerap masih dipegang oleh banyak keluarga.Berbeda dengan di Indonesia yang memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan, maka peranan perempuan di Indonesia bisa dikatakan jauh lebih baik. Banyak sudah perempuan Indonesia yang sukses dan memiliki peranan sama dengan kaum pria. Bukan hanya astronot perempuan yang dulu pernah kita miliki, namun kita juga memiliki Presiden dari kaum perempuan. Di bidang ekonomi, kita melihat Menteri Keuangan yang perempuan terbukti tangguh dan disiplin dalam melakukan pembenahan di jajarannya, termasuk menjaga ketahanan fiskal negeri ini.
Namun, dilihat dari kehidupan sosial secara umum, memang kaum perempuan Indonesia masih terpinggirkan. Dari jumlah penduduk miskin absolut di Indonesia, apabila dibedakan menurut jenis kelaminnya, maka penduduk perempuan miskin (16,72%) lebih banyak jumlahnya dibanding laki-laki (16,61%). Kalau kita merinci menurut rumah tangga, maka rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan, jumlahnya makin bertambah dari tahun ke tahun. Kemiskinan di Indonesia sangat lekat dan dekat dengan perempuan. Di sisi lain, dana BLT yang diterima dari Pemerintah sebagian besar diterima oleh laki laki, karena definisi kepala keluarga di Indonesia masih menempatkan laki-laki sebagai subjeknya. Tidak mengherankan jika perempuan di Indonesia identik dengan kemiskinan.
Mendefinisikan kaum perempuan memang sebuah hal yang sulit dan senantiasa menjadi perdebatan filsafat sepanjang zaman, mulai dari pemikir perempuan seperti Simone de Beauvoir, Kristeva & Irigaray, hingga Julia Kristeva, situasi kaum Perempuan kerap menjadi situasi problematik dan bukan afirmatif.
Namun satu hal yang jelas adalah bahwa bangsa ini tentu tak bisa berjalan tanpa perempuan. Dalam penentuan kebijakan makroekonomi, kaum ibu memiliki peran yang lebih besar dari kaum bapak. Andai para ibu rumah tangga mogok saja dalam sehari, atau berhenti membeli satu jenis barang secara serempak (yang sering terjadi), maka bermasalahlah perekonomian Indonesia.
Semoga semakin banyak perempuan Indonesia yang maju dan menjadi “Yamazaki-Yamazaki” di ruang angkasa, maupun di panggung lainnya.
Selamat berakhir pekan. Salam.